© 2004 Nyoman Utari Vipriyanti Posted , 23
April 2004
Makalah
pribadi
Pengantar
ke Falsafah Sains (PPS702)
Sekolah
Pasca Sarjana / S3
Institut
Pertanian Bogor
April 2004
Dosen:
Prof. Dr. Ir.
Rudy C. Tarumingkeng (penanggung jawab)
Prof. Dr. Ir.
Zahrial Coto
Dr Ir Hardjanto
PERAN SOSIAL CAPITAL INVESTMENT DALAM
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH
(Studi kasus di Propinsi
Bali)
OLEH:
NYOMAN UTARI VIPRIYANTI
P.063020031
PENDAHULUAN
Latar belakang
Pembangunan ekonomi suatu wilayah
dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ditujukan untuk mendorong masyarakat berpendapatan rendah mencapai suatu keadaan yang lebih baik. Hal tersebut
dapat dilakukan secara bertahap melalui tujuan jangka pendek yaitu
penurunan kemiskinan dan dalam jangka
panjang mewujudkan kesejahteraan.
Pembangunan ekonomi dibedakan dengan pertumbuhan ekonomi dimana pembangunan ekonomi lebih menekankan
pada proses yang tidak hanya mencakup
perluasan kuantitatif tetapi juga faktor
kualitatif seperti kelembagaan, organisasi dan budaya dimana
ekonomi tersebut diterapkan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi hanya
menekankan pada perluasan kuantitatif dalam variabel ekonomi seperti Gross National Product (GNP) dan Net National Product (NNP).
Tingkat
pertumbuhan ekonomi tinggi yang disertai dengan penurunan angka kemiskinan pada
periode 1965-1990an terjadi di Indonesia dan negara-negara Asia Timur lainnya
yang dikenal dengan istilah miracle
growth (Bhanoji Rao, 2001). Penyebab
terjadinya miracle growth adalah
tingkat investasi yang tinggi dalam physical
dan human capital, pertumbuhan yang
cepat dari produktivitas pertanian, orientasi ekspor, penurunan fertilitas,
manajemen ekonomi makro yang logis yang membantu mempromosikan saving dan investasi, serta intervensi
pemerintah dalam mempromosikan pembangunan industri spesifik. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini diharapkan
akan membawa dampak positif pada penyediaan tenaga kerja sehingga terjadi
konvergensi dalam tingkat pendapatan masyarakatnya.
Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi
oleh sistem perencanaan pembangunan yang dipilih. Ekonomi klasik menyatakan bahwa sumber daya alam merupakan mesin dari pertumbuhan
ekonomi yang kemudian terbantahkan melalui hasil penelitian Ortega dan
Gregorio, 2002, yang menyatakan bahwa
keberlimpahan sumber daya alam dapat memberikan dampak negatif bagi suatu
wilayah bila tidak diikuti dengan ketersediaan sumber daya manusia yang
berkualitas. Tingkat pertumbuhan
merupakan hasil interaksi antara sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber
daya fisik dan sumber daya sosial yang tersedia di wilayah tertentu. Berbeda dengan pendapat terdahulu yang
kurang memperhatikan variabel kelembagaan dalam pertumbuhan ekonomi, Johnson,
J. D., 2001, menekankan pentingnya berbagai variabel keterpaduan sosial seperti
kepercayaan, norma dan jaringan kerja sama dalam pertumbuhan ekonomi. Variabel tersebut berhubungan secara positif
yang artinya semakin tinggi kepercayaan, norma dan semakin baiknya jaringan
kerjasama akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Prilaku yang menunjukkan rasa percaya dan
kerjasama merupakan pandangan yang menonjol dalam interaksi ekonomi di negara
kaya dan miskin. Namun, peran dari rasa
percaya tersebut berbeda-beda secara kualitatif pada setiap tahap pembangunan
yang berbeda. Di negara Asia Selatan dan
Sub-Saharan Africa, sebagian besar interaksi terjadi bila mereka saling kenal
satu dan lainnya dimana reputasi sangat mempengaruhi transaksi ekonomi. Hubungan kekeluargaan, keanggotaan dalam
partai politik atau organisasi keagamaan tumpang tindih dengan transaksi
ekonomi. Hubungan ini dapat
dieksploitasi untuk membuat sistem pertukarangan ekonomi bekerja lebih halus. Sebaliknya dengan interaksi di kota besar,
interaksi yang terjadi hanya disebabkan oleh aktivitasnya. Seorang pembeli dan seorang penjual hanya
berinteraksi sebatas aktivitas jual beli.
Berbagai krisis yang menimpa negara-negara di Asia
selatan membuka wacana baru dalam kaitannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
suatu wilayah atau suatu negara yaitu bahwa perbedaan tingkat pertumbuhan
ekonomi tidak dapat dijelaskan hanya oleh perbedaan dalam input tradisional
seperti tenaga kerja, lahan dan kapital fisik saja. Perhatian terhadap social capital yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan rumah
tangga dan perkembangan masyarakat serta bangsa mulai dicurahkan. Hal ini berimplikasi besar terhadap kebijakan
pembangunan. Saat ini terbangun keyakinan bahwa keahlian manusia dan
pembangunan infrastruktur fisik perlu dikomplemenkan dengan pembangunan
institutional sehingga seluruh keuntungan investasi dapat diperoleh.
Tingginya
pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode tahun 1990-an memperkuat
keyakinan akan pentingnya peran social
capital di negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan ternyata
hanya merupakan suatu bumble economi
yang sangat rentan terhadap eksternal shock.
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya keadaan tersebut adalah
adanya kebijakan-kebijakan salah arah (misleading) yang lebih menekankan pada
keuntungan tanpa memperhatikan eksternalitas dari adanya kebijakan
tersebut. Selain itu, menurunnya angka
kemiskinan tidak mencerminkan terjadinya konvergensi dalam tingkat pendapatan
masyarakat artinya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mampu
memecahkan masalah pemerataan pendapatan masyarakat.
Indonesia
terdiri dari 30 propinsi yang memiliki limpahan sumber daya yang
berbeda-beda. Beberapa propinsi memiliki
sektor basis pada aktivitas primer, sebagian lainnya memiliki sektor basis pada
aktivitas sekunder dan tertier.
Perbedaan struktur perekonomian wilayah dapat dipastikan mempengaruhi
tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.
Wilayah-wilayah dengan sektor basis di bidang jasa menunjukkan laju
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding wilayah yang berbasis aktivitas
sekunder apalagi primer. Namun seperti
dikemukakan sebelumnya bahwa sumber daya alam bukan satu satunya faktor penentu
pertumbuhan. Dalam keadaan tertentu
sumber daya alam yang berlimpah akan berbalik menjadi sumber malapetaka bagi
masyarakat. Beberapa penelitian yang
mendukung pendapat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah selain
ditentukan oleh limpahan sumber daya alam juga ditentukan oleh kualitas sumber
daya manusia yang tersedia. Ortega dan
Gregorio, 2002, menemukan fakta bahwa sumber daya alam memiliki dampak positif
terhadap tingkat pendapatan tetapi sebaliknya terhadap laju pertumbuhan.
Hanya negara
negara yang memiliki tingkat human
capital yang tinggi dapat mengatasi dampak negatif dari keberlimpahan
sumber daya alam. Hal ini berarti bahwa
pada wilayah yang identik, semakin tinggi net
investment yang dicurahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
semakin tinggi kemampuan wilayah tersebut mengelola limpahan sumber daya
alamnya yang pada akhirnya mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah. Lane dan Tornell, 1996, menambahkan bahwa
dampak negatif pada pertumbuhan ini disebabkan oleh lemahnya institusi yang
akhirnya menghasilkan ”voracity effect” melalui mana kelompok yang
berkepentingan menangkap rent dari
sumber daya alam. Selain itu, dampak negatif tersebut berkaitan dengan alokasi
sumber daya pada berbagai aktivitas dengan spill-overs
yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan agregat.
Berdasarkan rangking
IKM (Indeks Kemiskinan Manusia) yang disusun oleh BPS, Bappenas dan UNDP, 2001,
ditunjukkan bahwa wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki limpahan sumber
daya alam tinggi (Papua, NTT, Kalimantan, Sulawesi) ternyata memiliki IKM yang
tinggi artinya di wilayah tersebut tersedia lebih sedikit pilihan dan
kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
IKM dihitung berdasarkan indikator deprivasi yang paling mendasar
seperti berumur pendek, ketersediaan pendidikan dasar, serta akses terhadap
sumber daya publik dan sumber daya privat.
Keadaan ini tentu menjadi paradoks dimana masyarakat yang seharusnya
memiliki pilihan dan kesempatan lebih banyak karena dilimpahi oleh sumber daya
alam ternyata sebaliknya tidak memiliki akses kepada sumber daya tersebut.
Rumusan Masalah
Telah diakui dunia bahwa Indonesia adalah negara
kepulauan yang memiliki keberlimpahan dalam sumber daya alam, sumber daya
manusia dan juga sumber daya sosial.
Eksploitasi terhadap sumber daya alam selama tahun 1970-1990 telah
menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga menjadi salah
satu negara terkemuka di kawasan asia tenggara dan disegani oleh dunia. Namun tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
tersebut ternyata tidak disertai dengan pemerataan pendapatan. Beberapa faktor yang diduga menyebabkan hal
tersebut adalah (1) Sistem perencanaan
pembangunan yang menganut adanya trade
off antara pertumbuhan dan pemerataan, (2) besarnya investasi yang tidak
seimbang diantara sumber daya fisik, sumber daya manusia dan sumber daya
sosial, (3) Tingginya tingkat
pertumbuhan disebabkan oleh tingginya tingkat konsumsi bukan oleh tingginya
tingkat investasi.
Adanya krisis
mata uang yang diikuti dengan krisis kepercayaan menyebabkan perekonomian
Indonesia berada dalam keadaan yang terpuruk.
Hingga saat ini, usaha pemulihan sudah banyak dilakukan tetapi Indonesia
belum mampu kembali kepada kinerja perekonomian sebelumnya. Dibutuhkan waktu yang lebih panjang bagi
Indonesia untuk dapat mencapai keadaan semula dibandingkan negara Asia lainnya
seperti Cina, Korea maupun Malaysia yang telah mampu membangun kembali
perekonomiannya.
Lambatnya kebangkitan kembali pertumbuhan ekonomi di
Indonesia ini mengingatkan bahwa teori ekonomi klasik yang menekankan pada
akumulasi kapital perpekerja sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi wilayah
tidak dapat lagi dipertahankan.
Demikian pula dengan teori pertumbuhan endogenous kini dirasakan tidak
mampu lagi terutama menggambarkan perbedaan pertumbuhan ekonomi wilayah setelah
terjadinya krisis kepercayaan. Ada satu
faktor yang terabaikan dalam proses pemulihan ekonomi di Indonesia yaitu peran
social capital sebagai hasil dari
interaksi antar sumber daya manusia.
Sebagaimana ditekankan oleh teori new
institution economi. Menurut Putnam
(1993) dalam suatu masyarakat yang memiliki stock social capital horisontal yang lebih besar akan memiliki hasil
pembangunan yang lebih baik. Warner,
2001, menyatakan pernyataan tersebut berimplikasi bahwa social capital dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan
efektivitas pemerintahan.
Permasalahannya adalah bagaimana memahami peran social capital dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, indikator apa
yang dapat digunakan untuk menilai keberadaan social capital tersebut dan bagaimana mengukurnya.
Tujuan
Secara umum paper ini bertujuan untuk menarik benang
merah yang dapat menggambarkan peran social
capital dalam proses pembangunan ekonomi wilayah. Gambaran umum tersebut akan dicapai melalui :
1.
Pendefinisian
, karakterisasi dan pengelompokan social capital
2.
Pendeskripsian
peran social capital sebagai salah
satu modal pembangunan.
Paper ini
menekankan pada pendekatan deduktif terhadap peran social capital dalam
pembangunan ekonomi wilayah pada tingkat mikro, meso dan makro. Pembahasan akan ditekankan pada keadaan
perekonomian wilayah di Bali dengan pertimbangan masih kuatnya social capital di wilayah tersebut.
TINJAUAN PUSTAKA
Social Capital
Perdebatan mengenai social capital telah berlangsung
sejak dulu namun mulai memperoleh perhatian kembali ketika Robert Putnam
mempublikasikan buku berjudul Making Democracy Work: Civic Tradition in
Modern Italy (1993) serta America’s Declining Social Capital
(1995). Perdebatan terjadi tidak hanya
diantara ahli sosiologi tetapi juga antropologi, politik, dan ekonomi. Untuk memiliki social capital, seseorang harus berhubungan dengan orang lain dan
pada orang lain inilah sumber dari keuntungannya (Portes, 1998 dalam laporan
Bank Dunia). Coleman, 1990, menyatakan
bahwa sebagai atribut dari struktur sosial dimana seseorang ada di dalamnya, social capital bukanlah private property dari beberapa orang
yang memperoleh keuntungan dari terbangunnya sosial capital tersebut. Social
capital terbentuk hanya bila setiap orang berkontribusi. Narayan, 1997, menyatakan social capital melekat dalam struktur
sosial dan memiliki karakteristik public
good. Bank Dunia mendefinisikan social capital sebagai norma-norma dan
hubungan sosial yang melekat dalam struktur sosial dalam masyarakat yang
memungkinkan orang-orang untuk mengkoordinasikan kegiatan dan mencapai tujuan
yang diinginkan.
Lesser,
E.L., 2000, mendefinisikan social capital sebagai kesejahteraan
atau keuntungan yang terjadi karena adanya hubungan sosial antar individu. Dalam hubungan sosial ini ada tiga dimensi
utama yang mempengaruhi perkembangan dari keuntungan ini yaitu struktur
hubungan, dinamika interpersonal yang terjadi dalam struktur serta konteks dan
bahasa umum yang digunakan oleh individu dalam struktur.
Seperti halnya human
capital, social capital tidak memiliki tingkat depresiasi yang
diperkirakan. Social capital sama dengan ilmu pengetahuan yang selalu
berkembang dan menjadi lebih produktif
bila digunakan. Social capital perlu dipelihara agar tetap produktif. Tanpa curahan waktu, energi atau sumber daya
lain pada social capital, hubungan
antar individual cenderung akan terkikis oleh waktu seperti terjadinya oksidasi
pada sebatang besi. Adler dan Kwon,
seorang profesor pada university of
southern california dalam Lesser, E.L, 2000, mengatakan bahwa sosial capital adalah public good, tidak dimiliki oleh orang
tertentu tetapi tergantung dari seluruh anggota dalam suatu jaringan
kerja. Karena dia bersifat public good maka individu memiliki
kecenderungan untuk melalaikan kewajiban dalam memelihara keberlangsungannya,
mempercayakan pada anggota yang lain untuk jaminan pemeliharaannya. Social
capital dihasilkan melalui perubahan dalam hubungan antar orang yang
memfasilitasi suatu tindakan. Oleh
karena itu, social capital lebih
bersifat intangible berbeda dengan physical capital. Namun demikian, bersama-sama dengan human capital dan physical capital, social
capital memfasilitasi aktivitas yang produktif.
Putnam, 1995, mendefinisikan social capital sebagai karakteristik organisasi sosial yang
berbentuk jaringan kerja, norma dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi
terjadinya koordinasi dan kooperasi untuk terwujudnya mutual benefit. Rasa percaya akan memudahkan terjalinnya
kerjasama. Semakin tebal rasa percaya
pada orang lain semakin kuat kerja sama yang terjadi diantara mereka. Sesuai dengan pendapat Putnam, 1995, Kepercayaan sosial muncul dari hubungan yang
bersumber dari norma resiprositas dan jaringan kerja dari keterkaitan
warganegara. Dengan adanya rasa saling
percaya, tidak dibutuhkan aktivitas monitoring terhadap prilaku orang lain agar
orang tersebut berprilaku seperti yang diinginkan. Rasa saling percaya dapat dibangun namun
dapat pula hancur.
Konsep social
capital merupakan konsep yang relevan baik di tingkat mikro, meso dan
makro. Pada tingkat makro, social capital mencakup institusi
seperti pemerintah, aturan hukum, civil dan kebebasan politik. Pada tingkat meso dan mikro, social capital merujuk pada jaringan
kerja dan norma yang membangun interaksi antar individu, rumah tangga dan
masyarakat. Putnam (1993), menekankan
pada hubungan setara (horisontal) dimana anggota berhubungan dengan sesamanya
sedangkan Coleman (1988,1990) menyatakan
bahwa social capital dapat mencakup
hubungan vertikal yang dicirikan oleh adanya hubungan hirarkhi dan
ketidaksamaan distribusi kekuasaan antar anggota.
Norma yang dibangun dan disepakati bersama akan mendorong
individu untuk melakukan investasi pada aktivitas kelompok. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa saling
percaya bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama dimana masing-masing
individu akan bertanggung jawab terhadap manfaat bersama.
Output dari social capital dalam suatu masyarakat
dapat dikelompokkan menjadi consumption
benefit dan production benefit. Consumption
benefits berupa terciptanya peningkatan manfaat akibat adanya rasa saling
percaya dan komunikasi seperti perasaan nyaman bila bekerja atau tinggal di
lingkungan masyarakat yang kita percaya.
Production benefit terwujud
dalam bentuk biaya transaksi yang lebih rendah, koordinasi yang lebih baik dan economic externalities.
Sistem Perencanaan Pembangunan Wilayah
Perencanaan
pembangunan adalah suatu proses yang bersifat “siklus” berkelanjutan dan
merupakan suatu proses pembelajaran.
Rustiadi, E., et al, 2003 menyatakan bahwa ada 4 pilar yang harus
diperhatikan dalam perencanaan pembangunan wilayah yaitu (1) Inventarisasi, klasifikasi dan evaluasi
sumber daya, (2) Ekonomi, (3) Kelembagaan dan (4) Spasial. Perencanaan
memerlukan kemampuan untuk memahami apa yang terjadi di masa depan. (suatu
gambaran menyangkut masa depan), kemampuan untuk memahami bagaimana masa depan
bisa berbeda, dan kemampuan untuk menggambarkan alat untuk mencapai masa depan
yang diinginkan.
Sebagian besar perencana setuju bahwa proses perencanaan
adalah penting karena dapat memberikan suatu mekanisme bagi pelaku untuk
berfikir mengenai masa depan. Prosesnya
lebih penting daripada dokumen atau
rencana yang dihasilkan oleh proses perencanaan tersebut. Langkah-langkah
prinsip dalam proses perencanaan yang umum adalah : (1)
Pernyataan Tujuan dan Proyeksi, (2)
Intervensi pilihan, (3)
Implementasi. Pernyataan tujuan
membutuhkan visi mengenai bagaimana wilayah seharusnya terlihat pada saat yang
akan datang. Tujuan masa depan seharusnya
berdasarkan pada pemahaman yang realistis mengenai apa yang mungkin terjadi
bukan daftar harapan. Intervensi
dibutuhkan untuk mengubah outcome.
Akhirnya proses implementasi akan mengumpan balik rencana sehingga bisa
diperbaiki untuk mencerminkan perubahan keadaan (Blair, 1991)
Berbagai
wilayah memiliki master plan yang menetapkan tujuan di masa yang akan
datang. Master plan hanya memberikan
gambaran kuat mengenai tujuan pengembangan fisik tetapi lemah dalam
menggambarkan tujuan sosial. Tujuan
harus dikembangkan dari keadaan komuniti
tersebut dan realistis. Pemilihan tujuan
pada perencanaan pemerintah lebih sulit dilakukan dibandingkan pada perencanaan
swasta. Perusahaan swasta seringkali
memiliki tujuan yang jelas yaitu profit atau kesejahteraan pelakunya sedangkan
pemerintah memiliki berbagai tujuan dimana terdapat persaingan keinginan dalam
komunitas.
Terminologi
pembangunan memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang, dalam setiap
aktivitas di setiap wilayah yang berbeda.
Oleh karena itu, harus ada batasan yang jelas mengenai istilah
pembangunan sehingga pengukuran keberhasilan pembangunan tersebut dapat
dilakukan. Secara tradisional,
Pembangunan dinyatakan sebagai kapasitas
dari ekonomi nasional dimana kondisi awal perekonomian yang statis menghasilkan
dan mempertahankan peningkatan dalam GNP maupun GDP (Todaro,2000).
Sejak tahun 1970-an, pembangunan ekonomi didefinisikan
kembali dalam konteks pengurangan atau peniadaan kemiskinan, ketidakmerataan,
dan pengangguran. Di masa lampau, pembangunan
ekonomi lebih menekankan pada rencana peningkatan produksi dan tenaga kerja sehingga kontribusi
pertanian menurun dan kontribusi sektor industri dan jasa meningkat. Strategi pembangunan selalu mengutamakan
percepatan industrialisasi yang seringkali mengorbankan pertanian dan
pembangunan pedesaan. Akhirnya,
prinsip-prinsip ekonomi yang mengukur pertumbuhan dilengkapi pula oleh
indikator sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pemukiman dan
sebagainya (Todaro, 2000).
Pembangunan tidak
akan memberi arti walaupun pendapatan perkapita meningkat dua kali lipat tetapi
mewujudkan keadaan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Pada tahun 1960 hingga 1970-an, sejumlah
negara memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi tetapi hanya
menunjukkan perbaikan yang kecil bahkan sama sekali tidak ada perbaikan dalam
mengatasi pengangguran, ketidakadilan, dan pendapatan riil dari 40 % populasi
penduduk miskin (Todaro, 2000).
Wilayah
bukanlah sekedar suatu areal yang diberi batas tertentu yang identik dengan
suatu wilayah administratif tetapi menyangkut suatu arti tertentu yang
dikaitkan dengan adanya permasalah-permasalahan yang relevan seperti pedesaan,
Kawasan Timur Indonesia, Daerah Aliran Sungai (DAS), perkotaan, pegunungan atau
yang lainnya (Rustiadi E., et al,
2003). Pedesaan adalah suatu wilayah yang dicirikan dengan
keadaan yang terisolir, miskin, bodoh, kekurangan infrastruktur, ketiadaan
informasi sehingga memiliki bargaining position yang lemah (Anwar, 2002).
Sistem perencanaan
pembangunan harus memperhatikan tiga aspek yaitu : Eficiency,
Equity dan sustainability. Aspek efisiensi akan
terpenuhi bila sistem perencanaan pembangunan tersebut dapat mewujudkan suatu keadaan yang lebih baik bagi
masyarakat dengan biaya korbanan yang sekecil mungkin. Implikasi dari keadaan ini bahwa sistem
perencanaan pembangunan harus dapat menekan biaya transaksi yang sering kali
muncul dalam proses pelaksanaannya. Aspek
equity bermakna bahwa sistem
perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan keragaman antara daerah,
golongan, suku, agama, gender sehingga hasil hasil pembangunan terdistribusi
dengan adil dan tidak bersifat bias. Aspek sustainability
merupakan satu hal yang tidak dapat diabaikan lagi. Tidak boleh ada trade-off diantara ketiga aspek tersebut.
Sistem
perencanaan pembangunan harus mampu menekan marginal
rate of time preference pemerintah dan masyarakat sehingga semua pihak
memiliki kesabaran tinggi dalam prilaku mengkonsumsi sumber daya alam yang ada
untuk tujuan pembiayaan pembangunan. Rendahnya marginal rate of time preference ditunjukkan oleh kecenderungan untuk mengkonsumsi sumber daya secara bijaksana. Model perencanaan pembangunan di masa depan harus
merupakan suatu model yang dibangun atas dasar
partisipatif masyarakat lokal karena hanya
masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam
tersebut yang memiliki insentif untuk menjaga keberlangsungannya.
Sistem perencanaan
pembangunan yang baik tidak selalu harus
merupakan model baru melainkan harus merupakan model yang paling tepat
untuk mencapai tujuan karena Sesuatu yang baru akan membutuhkan
waktu dan biaya penyesuaian yang tinggi dan belum
tentu tepat. Sesuatu
yang tepat dapat dibuat dari perbaikan-perbaikan holistik dan konsisten dari
apa yang telah ada. Selama ini
perencanaan pembangunan wilayah pedesaan di Indonesia bersifat sentralistik
walaupun telah ditetapkan undang-undang
otonomi daerah, perencanaan pembangunan wilayah pedesaan tetap saja dilakukan
oleh pemerintah daerah kabupaten kota.
Hal ini berarti bahwa desentralisasi hanya diartikan sebagai pelimpahan
wewenang pusat ke kabupaten/kota bukan kepada masyarakat. Fenomena ini tentu saja tidak merubah keadaan
wilayah pedesaan menuju suatu perbaikan, karena masih banyak perencana
pembangunan yang tidak mampu menangkap aspirasi masyarakat di pedesaan. Sebagai contoh pemberian kapal modern untuk
penangkapan ikan kepada masyarakat di
Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Hingga
saat ini bantuan tersebut tidak memberikan manfaat yang maksimal karena
masyarakat tidak memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk menggunakannya
sehingga menjadi bantuan yang tidak bermanfaat.
Banyak lagi contoh kegagalan bantuan pemerintah yang direncanakan tanpa
menyertakan masyarakat.
Teori Pertumbuhan
Teori pertumbuhan
ekonomi selalu berkembang sejak dikemukakan oleh kaum klasik yang dipelopori oleh Adam Smith (1776)
dan Ricardo (1817). Kelompok ini menekankan
bahwa sumber pertumbuhan ekonomi yang mendasar adalah pertumbuhan tenaga kerja
dan akumulasi kapital dimana campur tangan pemerintah sangat ditentang. Kelompok
klasik juga menyatakan bahwa peluang pertumbuhan produktivitas sektor pertanian
akan relatif lebih terbatas dibandingkan dalam industri. Pasar akan selalu mencapai keseimbangannya
sendiri karena ada invisible hand
sehingga alokasi sumber daya akan efisien.
Kaum klasik tidak mempertimbangkan adanya eksternalitas dan biaya
transaksi yang timbul karena informasi yang asimetris. Selain itu, perekonomian tidak selalu dalam
keadaan full-employment.
Adanya kegagalan pasar yang disebabkan oleh faktor eksternalitas dan informasi yang asimetris menyebabkan harga tidak mampu menunjukkan besarnya biaya produksi. Oleh karena itu muncul kelompok Keynesian yang menyatakan pentingnya campur tangan pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar. Kelompok ini muncul akibat adanya great depression pada tahun 1930-an. Model Harrod-Domar menggunakan konsep ekonomi Keynes dalam merencanakan pembangunan suatu wilayah dimana pertumbuhan yang cepat dapat diperoleh melalui peningkatan yang berkelanjutan dari tingkat tabungan dan investasi.
Namun terdapat kelompok skeptis yang berpendapat bahwa tingkat tabungan merupakan kunci dari transisi pertumbuhan
yang lambat menuju pertumbuhan yang cepat. Kelompok
ini disebut Neo-klasik yang dimotori oleh Robert M. Solow (1956) dan Trevor W.
Swan (1956). Solow menyatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor teknologi. Agregat fungsi produksi berada pada skala constant return yang mensubstitusi
antara dua input, kapital dan tenaga kerja.
Salah satu model neo-klasik
Solow-Swan yang tidak dapat disangkal adalah steady state
growth. Model ini mengasumsikan bahwa sejumlah output
diinvestasikan kembali dalam jumlah konstan.
Suatu negara yang secara permanen dapat meningkatkan tingkat tabungannya
akan memiliki tingkat output yang tinggi tetapi negara tersebut tidak akan
mencapai tingkat pertumbuhan output yang permanen. Implikasinya bahwa perubahan teknologi
merupakan sumber utama dari pertumbuhan.
Romer (1983, 1994) menunjukkan tidak adanya bukti dari
konvergensi steady state growth diantara
negara maju, selain itu, tidak terdapat alat yang bisa menggambarkan perbedaan
tingkat pertumbuhan pendapatan antar negara.
Romer berpendapatan bahwa model keseimbangan dari perubahan teknologi
endogenous disebabkan oleh akumulasi ilmu pengetahuan agen-agen yang
memaksimalkan keuntungan dan forward
looking.
Aliran baru
ini dikenal sebagai new growth economics
yang bertujuan untuk membangun model yang dapat menjamin bahwa tingkat pertumbuhan
pendapatan jangka panjang tergantung dari kebijakan fiskal, perdagangan luar
negeri dan kependudukan selain pada fungsi produksi dan utilitas. Model Romer mengabaikan asumsi neo-klasik yaitu perfect competitition dan
menambahkan asumsi constant atau increasing return of capital. Implikasinya adalah keseimbangan
pasar bersifat suboptimal karena efek eksternal
dari akumulasi ilmu pengetahuan tidak diperhitungkan oleh perusahaan dalam mengambil keputusan produksinya. Implikasi
lain, factor share tidak dapat
digunakan untuk mengukur kontribusi kapital dan tenaga kerja.
Lucas (1988)
mengajukan alternatif kedua terhadap model neo-klasik dimana sumber daya manusia sebagai mesin pertumbuhan
ekonomi. Ada dua model yang diajukan
yang tergantung dari cara output akhir dihasilkan. Model pertama, schooling model, menekankan bahwa pertumbuhan human capital tergantung dari bagaimana pekerja mengalokasikan
waktu antara produksi saat ini dan akumulasi human capital. Model kedua, learning by doing, pertumbuhan human capital adalah fungsi positif dari
usaha yang dicurahkan untuk memproduksi barang baru. Pada kedua model tersebut dimasukkan efek
internal dari produktivitas tenaga kerja, efek eksternal dari skala ekonomi dan
penguatan produktivitas dari faktor produksi lainnya.
PEMBAHASAN
Pertumbuhan Ekonomi Bali
Indonesia
sebagai negara berkembang yang mengalami beberapa dekade krisis, mulai merevisi
kebijakan-kebijakannya terutama perencanaan pembangunan yang awalnya bersifat sentralistik
menjadi desentralisasi. Kegagalan sistem
pemerintahan yang bersifat sentralistik dalam memfasilitasi masyarakat menuju
pemerataan, memerangi kemiskinan mendorong lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Penerapan otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan
masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat daerah. Peralihan kewenangan ini diharapkan memberi
dampak positif yang maksimal terhadap pengembangan sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri dan jasa.
Pemerintah kabupaten/kota harus belajar dari kesalahan
sistem perencanaan terdahulu yang bersifat sentralistik dan terlalu menekankan
pada aspek fisik. Harus ada reorientasi
mengenai pentingnya prinsip-prinsip perencanaan partisipatif karena selama ini proses perencanaan
partisipatif dianggap membutuhkan biaya tinggi padahal sesungguhnya terjadi
sebaliknya dimana proses perencanaan partisipatif dapat menekan adanya konflik
kepentingan yang merusak tatanan sosial ekonomi masyarakat dan degradasi sumber
daya serta lingkungan.
Demikian pula
dengan kabupaten/kota yang ada di Propinsi Bali. Sebagai salah satu propinsi di Indonesia,
Bali memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil namun krisis yang melanda
Indonesia terutama pada tahun 1998 tetap saja berdampak terhadap perekonomian
Bali. Turunnya laju pertumbuhan ekonomi
Indonesia tahun 1998 diikuti pula oleh turunnya laju pertumbuhan perekonomian
Bali namun demikian laju pertumbuhan ekonomi Bali masih berada diatas laju
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini berarti bahwa sektor perekonomian di
Bali relatif lebih kuat menghadapi pengaruh eksternal. Sebaliknya ketika terjadi shock akibat bom bali tahun 2002,
pertumbuhan ekonomi Bali turun mencapai
3, 15 persen dibawah pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 3,66
persen. Perbandingan pertumbuhan ekonomi
Bali dan Indonesia tahun 1998 hingga 2002 disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Indonesia Tahun
1998 – 2002
|
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Bali |
-4,04 |
0,67 |
3,05 |
3,39 |
3,15 |
|
Indonesia |
-13,68 |
0,23 |
4,77 |
3,32 |
3,66 |
Sumber : PDRB Propinsi Bali, 2003
Berpijak dari tahun 1999 yang dipertimbangkan sebagai
saat awal kebangkitan kembali perekonomian Bali maka tidak terlihat pola
pertumbuhan ekonomi klasik maupun neo klasik dimana pertumbuhan ekonomi
didorong hanya oleh ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang
berkualitas. Tabel 2. menggambarkan
beberapa indikator kabupaten/kota di Bali yang dapat menjelaskan bahwa terdapat
pola yang tidak teratur dari keragaan perekonomian antar kabupaten/kota
tersebut dimana terdapat wilayah kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan
tinggi tetapi bukan karena kontribusi sektor primernya yang merupakan indikator
berlimpahnya sumber daya alam seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut bukan pula
disebabkan oleh pembangunan manusianya karena terdapat beberapa kabupaten yang
memiliki nilai IPM menengah kebawah dengan laju pertumbuhan diatas rata-rata
atau sebaliknya nilai IPM menengah keatas dengan laju pertumbuhan dibawah
rata-rata (Jembrana, Tabanan dan Badung).
Peran sumber daya alam dan sumber daya manusia kemudian
dipertanyakan. Besarnya kuantitas sumber
daya alam dan sumber daya manusia ternyata tidak cukup untuk dapat mendorong
terjadinya pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.
Ada satu aspek yang tidak terbangun dengan baik sebagai modal dalam
pembangunan ekonomi yaitu social capital
yang mencakup elemen kepercayaan, norma dan jaringan kerja. Social
capital yang baik seperti adanya pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat
membangun ekspektasi pelaku pembangunan sehingga dapat meningkatkan
produktivitasnya.
Tabel 2. Keragaan Pertumbuhan PDRB per Kabupaten di
Bali Tahun 1999
|
|
Jembrana |
Tabanan |
Badung |
Gianyar |
Klung-kung |
Bangli |
Karang Asem |
Buleleng |
Denpasar |
Bali |
|
Growth rate (1999) |
0.9 |
0.58 |
0.57 |
1.76 |
0.89 |
0.46 |
0.71 |
1.08 |
1.44 |
0.67 |
|
Kontribusi sektor primer thp
PDRB (%) |
28.80 |
34.46 |
7.15 |
16.90 |
34.07 |
32.19 |
36.22 |
31.09 |
8.92 |
20.26 |
|
IPM (1999) |
65.5 |
68.7 |
68.2 |
64.4 |
62.9 |
64.4 |
57.5 |
63.1 |
72.1 |
65.7 |
|
Pengeluaran riil per-kap (1999) |
583.67 |
595.01 |
588.14 |
582.39 |
587.18 |
588.86 |
578.01 |
583.98 |
595.65 |
587.9 |
|
PDRB per-kapita,1999 (ribu
rupiah) |
4306,1 |
3706,7 |
8937,0 |
4985,9 |
4477,9 |
3589,0 |
2829,8 |
3105,1 |
5926,0 |
4790,3 |
|
IKM (1999) |
20.6 |
15.6 |
23.8 |
20.8 |
19.0 |
19.5 |
27.8 |
18.1 |
16.5 |
18.7 |
|
IPJ (1999) |
60.1 |
64.1 |
61.3 |
57.6 |
58.0 |
62.0 |
54.1 |
53.8 |
65.1 |
60.4 |
Sumber : PDRB Bali, 2003
Kelembagaan
tradisional seharusnya menjadi komplemen dari kelembagaan modern yang dibangun
pemerintah. Demikian pula yang terjadi
dalam perjalanan pembangunan di Bali, masyarakat bali tidak mengganti
kelembagaan tradisional dengan kelembagaan modern yang dibangun oleh
pemerintah. Keadaan ini diperkuat oleh
jiwa keagamaan yang melekat pada organisasi tradisional tersebut. Hingga saat
ini organisasi tradisional masyarakat bali masih tetap kuat seperti banjar
adat, subak, sekehe walaupun demikian organisasi modern juga tetap
dihidupkan. Banyak penelitian
membuktikan bahwa kelembagaan tradisional lebih arif dalam memahami konflik
pengelolaan sumber daya di wilayahnya karena lebih memahami perilaku masyarakat
sekitar sumber daya tersebut.
Bali terkenal
dengan keindahan alam dan pariwisata budaya yang terjaga oleh kekuatan social capital masyarakatnya. Hingga saat ini, aktivitas kepariwisataan
tersebut masih menjadi andalan karena menjadi penyumbang utama dalam perekonomian
Bali. Hal ini berarti pemerintah harus
mampu menjadi fasilitator agar social
capital masyarakat tidak melemah oleh adanya kemajuan teknologi terutama
terkait erat dengan globalisasi. Upaya
memberdayakan masyarakat melalui kebijakan otonomi daerah tidak boleh
menimbulkan masalah egoisme regional melainkan mampu melebur egoisme sektoral
sehingga mampu meningkatkan kinerja perekonomian daerah.
Membangun Dan Menguatkan
Social Capital
Warner, M., 2001, mempertanyakan sebuah pertanyaan logis yang terkait dengan pengakuan terhadap peran social capital yaitu dapatkah social capital dibangun di wilayah dimana social capital masih sangat lemah?. Bagaimana peran pemerintah dalam proses peningkatan social capital dalam masyarakat?. Bentuk social capital yang horisontal mencakup ikatan sejajar antar individu dalam suatu masyarakat yang membantu menghasilkan keadaan sederajat dan struktur demokrasi yang kuat (Putnam, 1993). Hierarchical social capital menghasilkan hubungan patron client yang dapat melumpuhkan pembangunan (Duncan, 1992: Putnam, 1993; Portes and Sensenbrenner, 1993; Warner, 2001).
Bourdieu, 1986, menyatakan
bahwa membangun dan memelihara social capital bukan
sesuatu yang alamiah tetapi memerlukan investasi yang menghasilkan sejumlah pendapatan. Pada tingkat masyarakat, returns on investment (ROI) di bidang social capital lebih menyebar
dan tergantung pada reproksitas umum untuk menjamin
pendapatan investor.
Hal ini menyebabkan di wilayah-wilayah dimana
reproksitas lemah, pemerintah lokal dan penduduk lokal kurang berminat
melakukan investasi dalam social capital
tingkat masyarakat. Selain ROI,
dua hal lainnya yang juga penting dalam pembentukan social capital masyarakat adalah otonomi dan keterkaitan. Oleh karena itu, kekuatan desentralisasi
akan sangat membantu membentuk social
capital masyarakat.
Di Bali,
perbedaan pendapatan asli daerah (PAD) antar kabupaten dan kota mendorong
timbulnya rasa superioritas satu kabupaten terhadap yang lainnya. Hal ini tentunya tidak mendukung terbangunnya
social capital horisontal melainkan
sebaliknya dimana social capital
hierarkhial menjadi lebih kuat. Hingga
saat ini, desentralisasi yang dimaknai
sebagai otonomi di tingkat kabupaten menjadikan persaingan regional lebih kuat
dan cenderung melemahkan jaringan kerja antar wilayah kabupaten.
SUMBER MEKANISME OUTPUTS
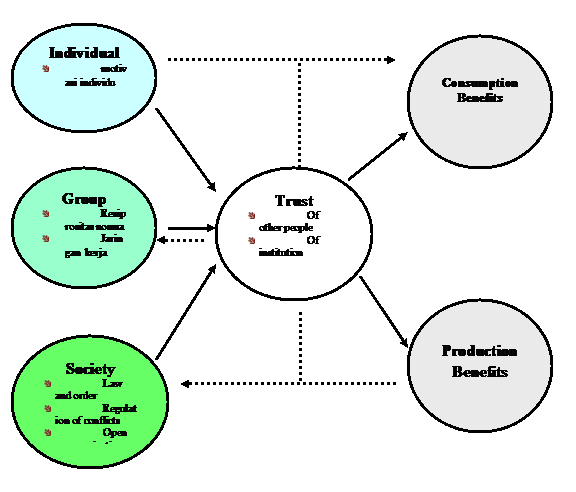
Gambar 1. Sumber dan Output dari Social Capital,
Ruuskanen (2001) dalam Reino Hjerppe,
2003
Gambar
1. menjelaskan mengenai sumber social capital terutama rasa saling
percaya di tingkat mikro (individual), meso (group) dan makro (society) yang
melalui mekanisme komunikasi dapat menimbulkan dua keuntungan yaitu consumption benefit dan production benefit. Seharusnya otonomi daerah yang bertujuan untuk
mendesentralisasi kekuasaan dapat meningkatkan social capital di seluruh
wilayah Bali tetapi kenyataannya otonomi daerah saat ini cenderung bertujuan
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berimplikasi pada
peningkatan biaya transaksi dan akhirnya dapat menekan pertumbuhan output.
Perubahan
struktur perekonomian Bali dari dominansi sektor primer menjadi sektor tersier
terutama sektor kepariwisataan menjadi pangkal permasalahan lain dalam
penguatan social capital
masyarakat. Dalam komunitas tradisional
pedesaan dimana aktivitas budidaya pertanian menjadi aktivitas utama banyak
kegiatan yang dilakukan bersama sehingga terdapat komunikasi yang
intensif. Sebaliknya dalam komunitas
modern yang bergerak di bidang jasa, komunikasi menjadi barang ekonomi dimana
untuk memperoleh komunikasi yang baik diperlukan pengorbanan baik dari sisi
waktu maupun biaya sehingga komunikasi antar masyarakat menjadi minimal. Perubahan struktur perekonomian ini tentu
akan berdampak pada melemahnya social
capital masyarakat. Oleh karena itu,
diperlukan peran pemerintah yang dapat menyesuaikan pada perubahan
tersebut. Modifikasi dari model
perubahan social capital masyarakat
yang dikemukakan Hjerppe, 2003 diilustrasikan pada gambar 2.
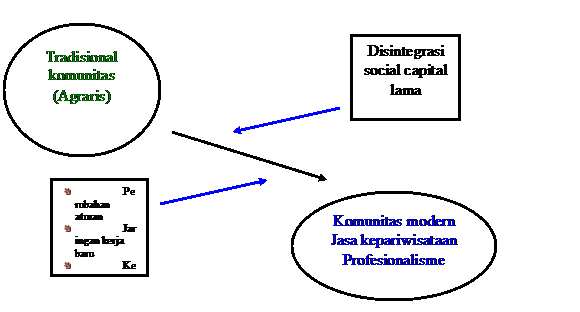
Sumber : Hjerppe, 2003
Gambar 2. Perubahan Social
Capital Masyarakat Bali
KESIMPULAN
Berdasarkan
kajian teoritis mengenai peran social capital dalam pertumbuhan ekonomi wilayah
dapat disimpulkan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi wilayah tidak hanya cukup
dibatasi pada sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia baik
kuantitas maupun kualitasnya melainkan harus mempertimbangkan tingkat modal
sosial (social capital) yang ada dalam masyarakat tersebut. Social
capital berperan tidak saja di tingkat mikro dan meso tetapi juga di
tingkat makro. Social capital masyarakat yang tinggi akan memberi keuntungan
produksi berupa rendahnya biaya transaksi dan keuntungan konsumsi berupa rasa
nyaman karena hidup dengan orang yang dapat dipercaya yang pada akhirnya dapat
meningkatkan produktivitas kerja.
Perekonomian
Bali yang relatif lebih stabil menjadi suatu pembenaran bahwa social capital yang berbasis pada norma,
jaringan kerja sama dan rasa percaya memberi kontribusi terhadap laju
pertumbuhan ekonomi regional. Salah satu
indikasi kuatnya social capital di Bali adalah banyaknya organisasi tradisional
masyarakat yang masih produktif seperti banjar, banjar adat, subak dan
sekehe-sekehe selain organisasi modern yang dibangun pemerintah. Pembenaran ini memang masih lemah karena
analisis yang dilakukan tidak bersifat kuantitatif. Namun demikian, peran social capital tidak dapat lagi diabaikan karena fakta telah
menunjukkan bahwa sumber daya fisik yang berlimpah dan sumber daya manusia yang
berkualitas tidak lagi mencukupi sebagai sumber pertumbuhan apabila tidak
terdapat norm, networks of cooperation
and trust.
DAFTAR PUSTAKA
Coleman, J. S. 1988. Social Capital in The Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, Volume 94.
Cristoforou, A. 2003.
Social Capital and Economic Growth:
The Case of
Hjerppe. 2003.
Social Capital and Economic Growth Revisited. Paper on Government institue for Economic research.
Johnson,
C. 2003.
A Model of Social Capital Formation.
Social Research and Demonstration Corporation Working paper Series
03-01.
Lin,
North,
D.C. 1990. Institutions,
Institutional Change and Economic Performance.
Putnam,
R.D. 1993. Making Democracy Work: Civic Tradition in
Modern
Romer, D. 1996.
Advance Macroeconomics. The McGraw-Hill Companies, Inc.
Ruttan V.W. 2002. Social Science Knowledge and Economic Development. SSKED-5, VWR Draft.
Warner, M. 2001. Building Social Capital : The Role Of Local Government. The Journal of Socio-Economics. North-Holland.
World Bank. 1998. The Initiative on defining, Monitoring and Measuring Social Capital. Overview and program Description. Social Development family. Environmentally and Socially Sustainable Development Network.